Talas (Colocasia esculenta (L.) Schott)
Talas (Colocasia esculenta (L.) Schott)
Talas merupakan salah satu jenis umbi-umbian yang termasuk jenis herba menahun. Di Indonesia, talas bisa dijumpai hampir di seluruh kepulauan dan tersebar di tepi pantai sampai pegunungan di atas 1.000 m dpl, baik liar maupun ditanam. Talas memiliki berbagai nama umum di seluruh dunia, yaitu taro, old cocoyam, abalong, taioba, arvi, keladi, satoimo, tayoba, dan yu-tao. Di Indonesia, talas juga memiliki berbagai nama daerah, seperti: eumpeu (Aceh), talo (Nias), bete (Manado dan Ternate), kaladi (Ambon) kaladi, kuladi, taleh (Minangkabau), keladi, talos (Lampung), bolang, taleus (Sunda), tales (Jawa), tales, kaladi (Madura), kladi, tales (Bali), aladi (Gorontalo dan Bugis), talak (Tolitoli), paco (Makassar), komo (Tidore) (Purnomo dan Purnamawati, 2007). Tanaman ini diklasifikasikan sebagai tumbuhan berbiji (Spermatophyta) dengan biji tertutup (Angiospermae) dan berkeping satu (Monocotyledonae).
Taksonomi tumbuhan talas adalah sebagai berikut (Rukmana, 1998):
Kingdom : Plantae
Divisi : Spermatophyta
Subdivisi : Angiospermae
Kelas : Monocotyledonae
Ordo : Arales
Famili : Araceae
Genus : Colocasia
Spesies : Colocasia esculenta (L.) Schott
Talas (Colocasia esculenta (L.) Schott) dibagi menjadi dua varietas, yaitu C. esculenta var. esculenta dan C. esculenta var. antiquorum. C. esculenta var. esculenta (disebut dasheen) diduga berasal dari kawasan tropik Asia Selatan dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia (Purseglove, 1975; Prana dkk, 2000). C. esculenta var. antiquorum (disebut dengan eddoe) berasal dari Cina dan Jepang. Varietas ini diduga merupakan hasil mutasi dan seleksi dari C. esculenta yang diintroduksi ke kawasan tersebut ratusan tahun yang lalu (Purseglove, 1975; Prana dkk, 1999).
Talas mempunyai variasi yang besar baik karakter morfologi seperti bentuk umbi, warna daging umbi serta kimiawi seperti rasa, aroma dan lain-lain. Karakter umbi talas diklasifikasikan sebagai berikut (Kusumo dkk., 2002):
– Bentuk umbi: kerucut, membulat, silindris, ellip, halter, memanjang, datar dan bermuka banyak, tandan, bentuk palu, lainnya.
– Warna daging umbi bagian tengah: putih, kuning muda, kuning atau oranye, merah, coklat, ungu.
– Warna serat daging umbi: putih, kuning muda, kuning atau oranye, merah, coklat, ungu, lainnya.
– Kelezatan daging umbi: hambar, dapat dirasakan, enak.
– Konsistensi daging umbi rebus: lengket, solid/padat, lunak, bertepung, lainnya.
– Aroma daging umbi rebus: non aromatik, aromatik.

Umbi talas memiliki keunggulan yaitu kemudahan patinya untuk dicerna. Hal ini disebabkan talas memiliki ukuran granula pati yang sangat kecil yaitu 1–4 μm. Ukuran granula pati yang kecil dapat bermanfaat mengatasi masalah pencernaan (Setyowati dkk.., 2007). Kandungan gizi umbi talas dapat dilihat pada Tabel berikut:
Tabel Kandungan Gizi Talas per 100 Gram Bahan
|
Kandungan Gizi (Satuan) |
Jumlah per 100 g bahan |
| Kalori (kal)
Protein (g) Lemak (g) Karbohidrat (g) Kalsium (mg) Fosfor (mg) Fe (mg) Pro Vitamin A (SI) Vtamin B1 (mg) Vitamin C (mg) Air (g) |
83,00 1,60 0,17 20,10 23,80 52,00 0,80 17,00 0,11 3,40 62,00 |
Sumber: Direktorat Gizi Depkes RI (1967) dalam Kasno dkk (2006)
Umumnya talas tidak dapat dikonsumsi secara langsung tanpa adanya pengolahan terlebih dahulu. Hal ini disebabkan kalsium oksalat yang terkandung di dalamnya dapat menyebabkan rasa gatal seperti pada mulut, lidah, dan tenggorokan. Kristal kalsium oksalat yang berbentuk seperti jarum tipis dapat menusuk dan berpenetrasi ke dalam lapisan kulit yang tipis, terutama yang terdapat di daerah bibir, lidah dan tenggorokan. Kemudian iritan (kemungkinan merupakan sejenis protease) akan muncul dan akan menyebabkan rasa tidak nyaman seperti gatal ataupun perih (Bradbury and Nixon, 1998). Selain kalsium oksalat, talas juga mengandung asam oksalat yang bersifat larut air. Asam oksalat dapat membentuk garam oksalat yang bersifat larut air maupun tidak larut air. Di dalam tubuh manusia, asam oksalat bersama dengan kalsium dan zat besi membentuk kristal yang tak larut sehingga dapat menghambat penyerapan kalsium oleh tubuh (Noonan and Savage, 1999).
Kandungan oksalat di dalam talas dapat dikurangi dengan berbagai macam cara sehingga talas aman untuk dikonsumsi. Salah satu cara untuk mengurangi kadar oksalat adalah dengan merendam talas dalam larutan garam, yaitu merendam talas dalam larutan NaCl 1% selama 20 menit yang dilanjutkan dengan pencucian (Tiastie dan Arik, 2003 dalam Yellashakti, 2008). Garam (NaCl) yang dilarutkan di dalam air akan terurai menjadi ion Na+ dan Cl–. Kalsium oksalat (CaC2O4) di dalam air akan terurai menjadi ion Ca2+ dan C2O42-. Na+ yang bermuatan positif akan mengikat C2O42- yang bermuatan negatif sehingga membentuk senyawa natrium oksalat (Na2C2O4). Begitu pula sebaliknya, ion Cl– akan mengikat Ca2+ dan membentuk senyawa kalsium diklorida (CaCl2). Kedua senyawa ini bersifat larut dalam air. Setelah perendaman, talas harus dicuci untuk menghilangkan sisa garam mineral dan endapan yang mungkin masih menempel pada talas.
Penurunan kadar oksalat juga dapat dilakukan dengan merendam talas dalam larutan NaCl dan dilanjutkan dengan pengukusan. Apriani dkk (2011) membuat tepung talas dengan cara merendam talas dalam larutan garam 10% yang dilanjutkan dengan pengukusan selama 20 menit. Setelah itu talas yang telah dikukus dikeringkan dan kemudian digiling. Pengukusan merupakan salah satu perlakuan fisik yang dapat mengurangi kadar oksalat karena pada suhu tinggi kalsium oksalat dapat terdekomposisi. Kalsium oksalat akan mulai terdekomposisi pada suhu 101.5°C dan menyublim pada suhu 149 – 160°C (NIOSH, 2005).
Fermentasi juga dapat mengurangi kadar oksalat pada talas. Penduduk Hawai terbiasa mengkonsumsi poi, yaitu suatu makanan yang terbuat dari talas terfermentasi. Cara membuat poi adalah umbi talas dikupas, direbus/atau sebaliknya direbus dahulu kemudian dikupas, dihaluskan, dicampur dengan air dan difermentasi selama beberapa waktu (umumnya semalam atau sampai dengan tiga hari). Rasa gatal pada talas tersebut dapat berkurang sebelum proses fermentasi yaitu selama proses perebusan dan saat fermentasi (Matthews, 2010). Oke dan Bolarinwa (2011) melakukan penelitian tentang tepung talas terfermentasi. Semakin lama waktu fermentasi, maka kadar kalsium oksalat semakin rendah. Setelah fermentasi 24 jam, kadar kalsium oksalat tepung turun 58%, sedangkan setelah fermentasi 48 jam, kadarnya turun 65%.

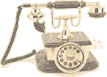
Recent Comments